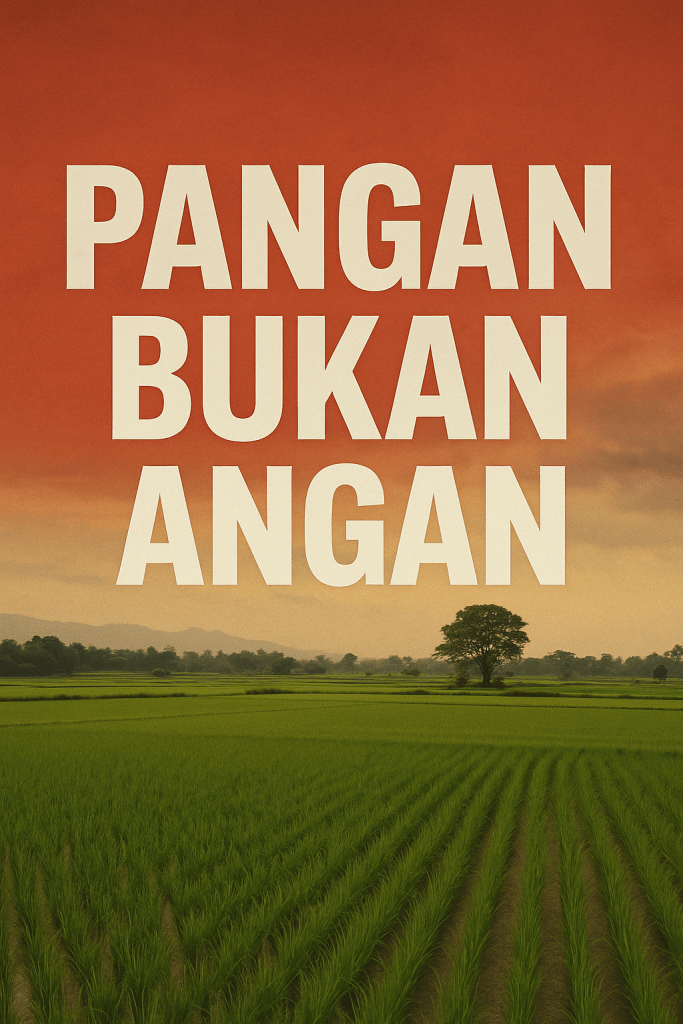
Setiap kali pemerintah berbicara tentang kedaulatan pangan, kita sering mendengar jargon-jargon indah: surplus beras, swasembada jagung, atau peningkatan produksi. Kata-kata itu terdengar manis, seperti dongeng sebelum tidur yang meninabobokan rakyat. Namun, ketika pagi tiba, realita di pasar dan dapur rakyat sering jauh berbeda. Harga beras tetap tinggi, minyak goreng tiba-tiba langka, cabai naik turun seperti roller coaster, dan petani masih bergelut dengan pupuk yang tak kunjung tersedia.
Pertanyaannya sederhana tetapi tajam: apakah pangan kita hanya sebatas angan, atau benar-benar menjadi kenyataan yang bisa dirasakan rakyat?
Surplus di Kertas, Krisis di Meja Makan
Mari kita bicara data. Pemerintah pada Agustus 2025 dengan bangga menyatakan bahwa Indonesia mengalami surplus beras hingga 13,78 juta ton sepanjang Januari–September (CNN Indonesia, 22/8/2025). Bahkan FAO memprediksi produksi beras kita mencapai 35,6 juta ton. Stok Bulog mencapai 3,9 juta ton—tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
Di atas kertas, ini prestasi luar biasa. Tetapi di pasar tradisional, harga beras medium justru menembus Rp 14.500–15.000 per kilogram (PIHPS Nasional, Agustus 2025). Rakyat kecil tetap harus merogoh kantong lebih dalam untuk membeli pangan pokok. Sementara itu, petani di Aceh mengeluh harga gabah anjlok saat panen raya, karena distribusi tidak seimbang. Surplus di gudang tidak otomatis berarti kenyang di meja makan.
Fenomena ini menunjukkan adanya jurang lebar antara data produksi dan realitas konsumsi. Angka surplus sering kali menjadi bahan konferensi pers yang membanggakan, tetapi rakyat hanya mengangkat alis sambil berkata: “kalau surplus, kenapa harga tetap mahal?”
Apakah kita rela pangan hanya menjadi angan-angan politik yang digaungkan setiap menjelang pemilu? Apakah kita puas dengan laporan surplus sementara anak-anak masih menderita stunting? Data SSGI 2022 mencatat prevalensi stunting nasional sebesar 21,6 persen, dengan Aceh bahkan mencapai 31,2 persen—salah satu tertinggi di Indonesia. Bagaimana mungkin kita berbicara surplus beras sementara generasi masa depan kita kekurangan gizi?
Bukankah ini sebuah ironi? Surplus beras di gudang negara, tetapi kekurangan gizi di tubuh anak-anak bangsa. Bukankah ini pertanda bahwa pangan kita masih sebatas angan, belum menjadi kenyataan?
Pangan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai martabat bangsa. Sebab makan bukan hanya soal kenyang, tetapi soal keberlangsungan hidup yang layak. Ketika rakyat harus antre minyak goreng, ketika petani tidak bisa membeli pupuk, ketika harga pangan naik tanpa kendali, maka sesungguhnya martabat bangsa sedang diuji.
Kedaulatan pangan tidak boleh hanya berarti angka surplus di statistik, tetapi harus hadir nyata di dapur keluarga, terutama keluarga miskin. Pangan bukan angan berarti memastikan setiap anak Indonesia mendapat akses pada nasi, telur, sayur, dan lauk yang bergizi tanpa khawatir harga melambung.
Dari Retorika ke Aksi
Jika pangan bukan sekadar angan, maka beberapa langkah harus berani ditempuh.
Pertama, reformasi distribusi pangan. Kita sudah terlalu sering mendengar cerita tentang beras Bulog yang menumpuk di gudang sementara pasar tetap mahal. Pemerintah harus mendekatkan gudang ke rakyat, memotong rantai distribusi yang panjang, dan memangkas permainan tengkulak yang mempermainkan harga. Digitalisasi rantai pasok bisa menjadi solusi—dari gudang hingga warung, masyarakat bisa memantau harga dan stok secara real time.
Kedua, pangan lokal harus diangkat. Jangan hanya bicara beras. Indonesia kaya pangan alternatif: sagu, jagung, ubi, pisang. Namun, semua itu masih dipandang sebagai pangan kelas dua. Jika kita serius, pangan lokal bisa menjadi benteng menghadapi krisis global. FAO memperingatkan bahwa perubahan iklim akan mengancam produksi padi. Maka diversifikasi pangan bukan pilihan, tetapi kebutuhan.
Ketiga, pendekatan gizi, bukan sekadar produksi. Produksi berlimpah tidak ada artinya jika tidak berdampak pada gizi masyarakat. Surplus beras tidak otomatis menurunkan stunting. Kita harus memastikan setiap program pangan terhubung dengan program gizi: distribusi telur, susu, ikan, dan sayur untuk keluarga miskin. Pangan bukan sekadar kuantitas, tetapi kualitas.
Peran Strategis Universitas Syiah Kuala (USK)
Di tengah problematika pangan ini, peran perguruan tinggi, khususnya Universitas Syiah Kuala (USK) di Banda Aceh, menjadi sangat penting. USK sebagai Jantong Hatee Rakyat Aceh bukan hanya pusat pendidikan, tetapi juga laboratorium sosial yang bisa menjembatani kebijakan dengan kebutuhan rakyat.
Pertama, USK berperan dalam riset dan inovasi. Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Fakultas Peternakan USK telah banyak menghasilkan riset terkait teknologi budidaya, pascapanen, serta sistem distribusi pangan. Inovasi seperti pupuk organik lokal, teknologi pengolahan pascapanen berbasis IoT, hingga sistem digital traceability bisa langsung diadopsi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan.
Kedua, USK berperan dalam pendampingan masyarakat. Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, mahasiswa USK telah terjun langsung ke desa-desa, mendampingi petani dan nelayan. Mereka membantu mengedukasi soal gizi, teknologi budidaya, hingga pemasaran produk. Pangan bukan angan ketika perguruan tinggi tidak hanya bicara teori di ruang kuliah, tetapi hadir nyata di sawah, ladang, dan dapur rakyat.
Ketiga, USK berperan dalam advokasi kebijakan. Dengan kapasitas akademiknya, USK dapat menjadi mitra kritis bagi pemerintah Aceh dan pusat. Misalnya, dengan memberikan masukan berbasis data tentang program pangan, evaluasi distribusi SPHP, atau strategi diversifikasi pangan lokal. Dalam hal ini, suara akademisi USK bisa menjadi penyeimbang antara retorika politik dan realita lapangan.
Aceh adalah barometer penting dalam isu pangan. Daerah dengan lahan pertanian luas, garis pantai panjang, dan kekayaan alam yang melimpah, justru masih menghadapi prevalensi stunting tertinggi. Ini menjadi tamparan keras bahwa persoalan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi soal distribusi, akses, dan keadilan.
Jika Aceh berhasil keluar dari jebakan stunting dengan mengelola pangan secara adil, maka Indonesia bisa belajar. Jika Aceh tetap terjebak pada surplus palsu dan gizi buruk, maka ini akan menjadi cermin buruk bagi negeri.
Penutup: Saatnya Membumikan Angan
“Pangan bukan angan” harus kita gaungkan bersama. Bukan sekadar slogan di spanduk atau jargon di konferensi pers, tetapi menjadi gerakan nyata yang melibatkan semua pihak: pemerintah, petani, akademisi, hingga masyarakat.
Pangan bukan angan ketika beras murah benar-benar ada di warung desa.
Pangan bukan angan ketika anak-anak tidak lagi stunting karena telur dan ikan terhidang di meja makan.
Pangan bukan angan ketika petani merasa sejahtera, bukan sekadar objek program.
Pangan bukan angan ketika universitas seperti USK terjun langsung, menghadirkan solusi berbasis ilmu untuk rakyat.
Indonesia tidak butuh janji surplus, tetapi butuh bukti kenyang. Tidak butuh jargon kedaulatan, tetapi butuh distribusi yang adil. Tidak butuh angka statistik, tetapi butuh anak-anak sehat yang berlari di halaman sekolah.
Pangan bukan angan. Pangan adalah hak. Dan hak itu harus diwujudkan sekarang juga.
Sumber Data & Referensi
1. CNN Indonesia. (2025, 22 Agustus). Beras RI Tahun Ini Diproyeksi Melimpah, Surplus hingga 13 Juta Ton. Diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250822203947-92-1265466/beras-ri-tahun-ini-diproyeksi-melimpah-surplus-hingga-13-juta-ton
2. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Indonesia 2024. Jakarta: BPS RI.
3. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional). (2025, Agustus). Harga Beras Medium dan Premium di Pasar Tradisional.
4. Kementerian Pertanian RI. (2025). Laporan Ketersediaan dan Produksi Pangan Nasional 2025.
5. Food and Agriculture Organization (FAO). (2024). FAO Rice Market Monitor. Rome: FAO.
6. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
7. Bank Dunia. (2023). Indonesia Economic Prospects: Investing in Nutrition for Growth. Washington DC: World Bank.

Leave a comment